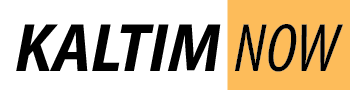Jakarta, Kaltimnow.id — Bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera kembali menyoroti persoalan klasik pengelolaan hutan dan lingkungan di Indonesia. Di saat yang hampir bersamaan, pemerintah justru gencar mempromosikan komitmen penurunan emisi dan perdagangan karbon di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil. Kontras inilah yang menjadi sorotan utama diskusi publik Forest Watch Indonesia (FWI) bertajuk “Di Belém Karbon Hutan Indonesia Dijual, Faktanya Sumatera Banjir Besar!” yang digelar di Salihara Art Center, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).
Dalam forum tersebut, FWI menilai narasi keberhasilan iklim Indonesia di panggung internasional belum sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Banjir besar yang berulang di Sumatera disebut tidak bisa dilepaskan dari deforestasi masif dan melemahnya fungsi daerah aliran sungai (DAS).
Peneliti dan Pengkampanye Hutan FWI, Tsabit Khairul Auni, mengungkapkan bahwa tutupan hutan Sumatera kini hanya tersisa sekitar 25 persen dan terus mengalami penurunan. Kondisi ini, menurutnya, berbanding lurus dengan meningkatnya kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi.
“Indonesia di Belém berbicara soal karbon dan pengurangan emisi. Namun di dalam negeri, lanskap yang rusak justru memicu banjir besar. Jika perlindungan hutan dan DAS tidak diperkuat, maka narasi karbon itu kehilangan makna,” ujar Tsabit.
Diskusi juga menyinggung lemahnya hasil konkret COP30 dalam menjawab tuntutan masyarakat adat dan masyarakat sipil. Meski diwarnai mobilisasi besar komunitas adat yang menuntut pengakuan hak kelola hutan, perundingan resmi dinilai belum menghasilkan keputusan tegas, baik soal penghentian deforestasi maupun perlindungan wilayah adat.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Eustobio Rero Renggi, menilai pengakuan wilayah adat seharusnya menjadi fondasi kebijakan iklim nasional. Ia menegaskan bahwa janji pemerintah untuk mengembalikan 1,4 juta hektare hutan adat perlu dibuktikan melalui kebijakan nyata.
“Masyarakat adat terbukti mampu menjaga hutan selama ratusan tahun. Tanpa pengakuan hak mereka, upaya menghadapi krisis iklim hanya akan berhenti pada jargon,” tegasnya.
Kritik tajam juga diarahkan pada skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang dijadikan salah satu instrumen utama pembiayaan iklim Indonesia. Menurut Torry Kuswardono dari Yayasan PIKUL, perdagangan karbon berpotensi menjadi ruang impunitas bagi industri ekstraktif yang seharusnya bertanggung jawab memulihkan ekosistem.
“Penurunan emisi yang diklaim lewat skema offset sering kali hanya terjadi di atas kertas. Di lapangan, kerusakan lingkungan tetap berjalan,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Tsabit yang menilai pasar karbon berisiko mengaburkan kewajiban negara dalam memenuhi target NDC. Tanpa regulasi yang tegas, hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekologis justru diperlakukan sebagai komoditas ekonomi.
Akademisi Universitas Indonesia, Dr. Mahawan Karuniasa, menambahkan bahwa komitmen iklim Indonesia hanya akan bermakna jika mampu menurunkan emisi secara nyata sekaligus mengurangi risiko bencana di dalam negeri. Ia juga menyoroti ketimpangan tanggung jawab global, di mana negara berkembang justru menanggung dampak paling berat dari krisis iklim.
Sementara itu, diskusi turut mengkritisi skema pendanaan adaptasi global yang masih didominasi utang. Fiorentina Refani dari CELIOS menilai pola tersebut justru berpotensi melahirkan beban baru bagi negara berkembang.
“Adaptasi iklim seharusnya melindungi masyarakat, bukan menjebak negara dalam utang baru,” tegasnya.
Banjir di Sumatera, menurut para pembicara, menjadi bukti bahwa krisis iklim bukan sekadar isu global, melainkan persoalan nyata di tingkat tapak. Selama perlindungan hutan, penguatan DAS, dan pengakuan masyarakat adat belum menjadi prioritas, maka komitmen iklim Indonesia berisiko hanya terdengar lantang di forum internasional, namun rapuh di rumah sendiri. (Ant)