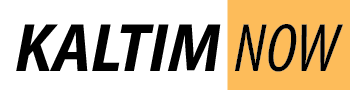Samarinda, Kaltimnow.id – Penetapan upah minimum selalu menjadi barometer keberpihakan negara terhadap pekerja. Setiap angka yang tercantum dalam Surat Keputusan gubernur bukan sekadar statistik ekonomi, melainkan penentu apakah buruh bisa hidup layak atau terus terjebak dalam lingkaran kekurangan.
Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur 2026, buruh kembali dihadapkan pada dilema klasik: angka ekonomi yang tampak menjanjikan di atas kertas, namun tak pernah cukup untuk menjawab realitas hidup sehari-hari.
Sebagai pijakan awal, UMP Kaltim 2025 ditetapkan sebesar Rp3.787.801. Berdasarkan skema Peraturan Pemerintah terbaru, kenaikan upah dihitung menggunakan formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alfa, dengan rentang alfa 0,5 hingga 0,9.
Sekilas, rumus ini tampak objektif dan ilmiah. Namun ketika ditelaah lebih dalam, formula tersebut justru menelanjangi jurang lebar antara kebijakan negara dan kebutuhan riil buruh.
Jika Gubernur Kalimantan Timur memilih “jalan paling dermawan” dengan menetapkan alfa tertinggi 0,9, maka UMP Kaltim 2026 diproyeksikan naik menjadi Rp4.018.099. Kenaikan sekitar 6 persen atau Rp230.298.
Masalahnya, kenaikan ini sudah tertinggal sejak garis start. Sepanjang 2025, harga kebutuhan pokok beras, minyak goreng, transportasi, hingga sewa rumah telah lebih dulu melonjak. Artinya, kenaikan tersebut bukanlah peningkatan kesejahteraan, melainkan sekadar tambalan atas kebocoran lama. Buruh tetap nombok.
Situasi menjadi jauh lebih buruk jika gubernur memilih alfa terendah 0,5. Kenaikan hanya sekitar 4 persen atau Rp157.572. Ini bukan lagi penyesuaian, melainkan pemiskinan yang dilegalkan secara administratif.
Ironi terbesar terletak pada posisi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL Kalimantan Timur 2025 tercatat sebesar Rp5.735.353—angka yang merepresentasikan standar hidup layak, bukan hidup mewah, dan disusun berdasarkan kebutuhan riil buruh.
Faktanya, UMP saat ini bahkan belum menyentuh 70 persen dari KHL. Selisihnya lebih dari Rp1,9 juta. Selama KHL terus diabaikan dalam penetapan upah, maka jargon keadilan sosial tak lebih dari slogan kosong.
Jika negara sungguh berpihak pada pekerja, KHL semestinya menjadi fondasi utama penetapan upah, bukan sekadar angka pelengkap yang setiap tahun dikesampingkan.
Data resmi menunjukkan inflasi Kalimantan Timur berada di angka 1,77 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 4,75 persen. Dengan indikator tersebut, tidak masuk akal jika buruh hanya “diganjar” kenaikan 4–6 persen.
Sebaliknya, tuntutan serikat buruh agar kenaikan upah berada di kisaran 8–10 persen justru lebih rasional dan berkeadilan. Kenaikan upah bukan ancaman bagi ekonomi daerah. Ia adalah motor penggerak konsumsi, memperkuat daya beli, menghidupkan UMKM, dan menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif.
Di kalangan serikat buruh, isu penggunaan alfa rendah telah memicu penolakan luas. Dewan Pengupahan Daerah tidak boleh terjebak menjadi sekadar stempel kebijakan pusat atau kepentingan pengusaha.
Perannya harus nyata: mempertahankan penggunaan alfa tertinggi, memastikan kenaikan UMP berdampak hingga UMK dan UMSK, serta yang paling penting mendengar suara buruh, bukan hanya tekanan modal.
Buruh Kalimantan Timur tidak anti-dialog. Namun sejarah panjang perjuangan perburuhan mengajarkan satu hal: ketika suara buruh diabaikan, aksi adalah jalan terakhir.
Jika tuntutan kenaikan 8–10 persen kembali ditutup telinga, maka aksi massa terbuka lebar, mogok kerja bisa menjadi pilihan, dan roda produksi berpotensi berhenti total.
Ini bukan ancaman, melainkan konsekuensi logis dari kebijakan yang menolak melihat realitas hidup pekerja.
Pada akhirnya, pilihan ada di tangan para pengambil kebijakan: berpihak pada buruh dan keadilan sosial, atau mempertahankan pertumbuhan semu yang dibayar mahal oleh keringat dan pengorbanan pekerja.
Opini: Yoyok Sudarmanto, Ketua Serikat Buruh Samarinda (SERINDA). (Ant)